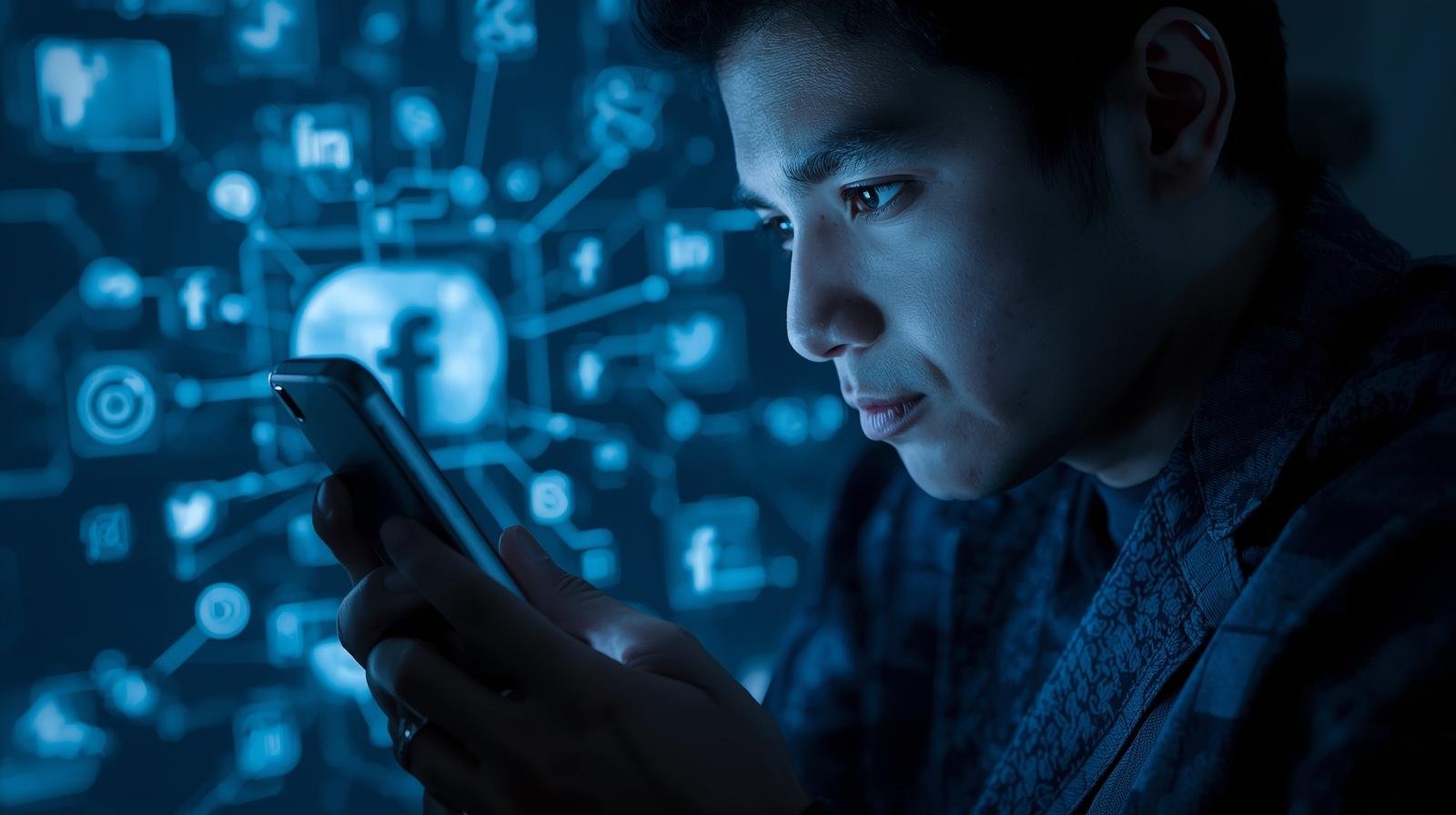Di era digital saat ini, dunia tampak seperti sebuah panggung besar dimana setiap individu berusaha menampilkan versi terbaik dari dirinya. Melalui media sosial, setiap momen, pencapaian, bahkan aktivitas rumit sekalipun dapat diubah menjadi suatu pertunjukan yang menarik perhatian. Namun di balik tampilan yang terlihat menarik, tersembunyi suatu fenomena yang semakin kuat terjadi terutama di kalangan Gen Z, yaitu narsistik, suatu kecenderungan untuk menonjolkan diri secara berlebihan demi mendapatkan validasi dari orang lain.
Narsistik sendiri adalah kondisi mental atau gangguan kepribadian (Narcissistic Personality Disorder atau NPD) yang membuat seseorang memiliki perasaan superioritas berlebihan, selalu membutuhkan pujian yang konstan, serta kurang mampu merasakan empati terhadap orang lain (Melia, 2024). Beberapa karakteristik yang sering terlihat adalah merasa bahwa dirinya sangat penting, memiliki kebutuhan untuk selalu mendapat perhatian, terlibat dalam hubungan yang bermasalah, dan sangat rentan terhadap kritik.
Fenomena ini bukan hanya sekadar tren perilaku semata, tetapi juga mencerminkan perubahan nilai dan cara hidup generasi saat kini. Banyak orang tanpa menyadari bahwa kebahagiaan mereka diukur dari jumlah “like” dan “followers”, seolah-olah harga diri hanya tergantung pada seberapa banyak orang yang mengakui kehadiran atau eksistensi dirinya.
Di tengah euforia digital seperti ini, Al-Qur’an sebenarnya telah memberikan kritik yang tajam sejak ratusan tahun lalu. Dalam QS. Al-Hadid ayat 20, Allah menggambarkan kehidupan dunia sebagai permainan, hiburan, perhiasan, serta ajang pamer antar manusia. Ayat yang menjadi titik pijak fenomena narsistik tersebut adalah:
اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِۗ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًاۗ وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌۙ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ۗوَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ
Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, kelengahan, perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kamu serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. (Perumpamaannya adalah) seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengering dan kamu lihat menguning, kemudian hancur. Di akhirat ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan keridaan-Nya. Kehidupan dunia (bagi orang-orang yang lengah) hanyalah kesenangan yang memperdaya. (QS. Al-Hadid [57]: 20).
Ayat ini memberikan gambaran mengenai realitas dunia, yaitu sesuatu yang sementara, mempermainkan, dan terkadang menipu. Kata “permainan” (la‘ib) dan “senda gurau” (lahw) menggambarkan berbagai aktivitas di dunia ini yang tidak lebih dari hiburan yang semu, yang bisa mengalihkan perhatian manusia dari tujuan yang sejatinya. “Perhiasan” (zinah) menunjukkan obsesi akan penampilan eksternal, sedangkan “bermegah-megahan” (tafākhur) menggambarkan sikap bersaing untuk terlihat lebih unggul dibandingkan dengan orang lain.
Jika konteks ini dilihat di zaman modern, media sosial merupakan representasi nyata dari ayat tersebut. Platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube menjadi tempat bagi manusia menampilkan kehidupan yang terlihat “ideal”, padahal sering kali tidak sesuai dengan kenyataan. Senyuman bahagia boleh jadi hanya menutupi rasa lelah yang tersimpan dalam hati.
Generasi Z tumbuh di tengah era dimana identitas digital lebih bermakna, bahkan lebih penting, daripada identitas dunia nyata. Psikolog menyebut fenomena ini sebagai “narcissistic display”, yaitu upaya terus-menerus untuk menunjukkan diri secara menarik agar menerima pengakuan sosial (April, 2008).
Yang menarik, budaya narsistik ini bukan sekadar menyatakan kesombongan, tetapi merupakan bentuk baru dari pencarian eksistensi. Ketika seseorang tidak mendapatkan pengakuan dari lingkungan sekitarnya, biasanya ia mencari validasi dari dunia maya. Likes dan views menjadi “nilai sosial baru” yang membentuk tingkat rasa percaya diri seseorang.
Namun Al-Qur’an memberikan peringatan: ketika manusia terlalu bergantung pada pengakuan dari dunia, ia kehilangan arah spiritualnya. QS. Al-Hadid [57]: 20 menyebutkan, “…seperti hujan yang tanamannya membuat para petani terpesona, kemudian tanaman itu menjadi layu dan kamu melihatnya kekeringan, lalu hancur berderai…” Perumpamaan ini menunjukkan bagaimana sesuatu yang awalnya menarik bisa cepat hancur. Seperti postingan viral di media sosial, yang hari ini digemari, besok bisa dilupakan.
Kritik Al-Qur’an terhadap budaya narsis tidak berarti Islam menolak keindahan atau ekspresi diri. Islam justru mengajarkan keseimbangan antara ekspresi luar (eksistensi) dan substansi batin (esensi). Masalah terjadi ketika ekspresi eksternal mengambil alih esensi internal, ketika seseorang terlalu sibuk membangun citra di depan orang, daripada membangun makna dalam diri sendiri.
Gen Z umumnya dianggap memiliki jiwa kreatif dan suka mengekspresikan diri. Namun, kemampuan tersebut bisa menjadi tidak bermakna jika tidak didukung oleh kesadaran spiritual yang memadai. Dalam konteks ini, Ayat 20 Surah Al-Hadid menjadi cermin untuk mengevaluasi: apakah kita hidup hanya untuk menunjukkan kehidupan kita, atau untuk memiliki makna yang lebih dalam?
Media sosial membuat kita lebih sering memikirkan bagaimana kita dilihat oleh orang lain daripada siapa kita sebenarnya. identitas kini lebih sering ditampilkan secara performatif, bukan dari hati yang autentik.
Banyak penelitian psikologi modern menunjukkan bahwa semakin tinggi seseorang terpapar media sosial, semakin tinggi peluang munculnya rasa cemas dan depresi. Mengapa? Karena budaya narsis menciptakan standar kebahagiaan yang tidak nyata. Orang merasa gagal ketika kehidupan mereka tidak secerah orang lain yang tampil di layar.
Inilah makna bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan. Permainan yang dimaksud adalah sesuatu yang membuat manusia lalai dari amal-amal yang mengarah ke akhirat. Ketika kesuksesan hanya dipamerkan untuk mendapat pujian, maka makna dari amal tersebut telah lenyap.
Ayat 20 Surah Al-Hadid [57] ditutup dengan pernyataan: “Dan di akhirat ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan keridhaan-Nya. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.” Ayat ini memberikan dua pilihan jalan: terus tenggelam dalam ilusi yang tidak memberi makna, atau kembali pada kesadaran yang benar-benar memandu kehidupan.
Kritik Al-Qur’an bukan hanya sekadar larangan, tetapi juga ajakan yang ingin menyadarkan manusia untuk memandang kehidupan dari perspektif yang lebih substansial. Media sosial tidak harus menjadi cermin narsisme; ia bisa menjadi wadah untuk dakwah, edukasi, dan ekspresi kreatif yang bermakna. Jika niat digunakan secara benar, eksistensi digital bisa sejalan dengan esensi spiritual manusia.
Al-Qur’an mengajak manusia untuk menyeimbangkan keduanya, antara eksistensi dan esensi. Boleh menampilkan diri di ruang publik, tetapi jangan sampai kehilangan arah spiritualnya. Di tengah dunia dimana seseorang sibuk membangun eksistensi dan citra diri, mari kita kembali ke esensi: menjadi manusia yang bermakna bukan karena tampilan, tetapi karena nilai yang kita bawa.
Referensi
Asnita, Melia. “Studi Literatur Penelitian Kesehatan Mental Individu yang Mengalami Narcissistic Personality Disorder (NPD).” Nathiqiyyah 7, no. 2 (2024): 118-133.
Bleske-Rechek, April, Mark W. Remiker, and Jonathan P. Baker. “Narcissistic men and women think they are so hot–But they are not.” Personality and Individual Differences 45.5 (2008): 420-424.